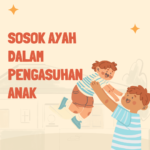Dalam tasawwuf dikenal luas gagasan tentang keagungan (jalal) dan keindahan (jamal) Tuhan. Dalam pandangan tasawwuf, Tuhan memiliki “wajah” ganda. Di satu pihak, Dia adalah Yang Maha Agung, tetapi di pihak lain Dia juga Maha Indah. Kedua dimensi ini tak terpisahkan, melainkan adalah dua sisi dari koin yang sama.
Meski demikian, yang terjadi dalam sejarah Islam, muncul kelompok-kelompok yang mengembangkan “cara beragama” yang menekankan salah satu dari dua dimensi ini. Ada yang tekanannya diarahkan pada dimensi jalal atau keagungan Tuhan, ada yang sebaliknya. Masing-masing cara ini tentu membawa akibat yang berbeda-beda.
Aspek keagungan Tuhan tampak dalam hukum syariat lahiriah yang memang, di permukaan, tampak keras dan “kaku”. Sementara dimensi keindahan Tuhan tampak dalam ajaran ilmu-ilmu kebatinan Islam atau tasawwuf yang menekankan kasih-sayang-Nya. Tak bisa ditutup-tutupi bahwa kaum sufi lebih tertarik untuk mengeksplorasi dimensi keindahan Tuhan ini ketimbang dimensi “jalal”-Nya.
Karena itu maqam mahabbah (cinta) adalah salah satu maqam atau tingkatan spiritual yang paling banyak mendapatkan perhatian para sufi Islam, terutama pada awal-awal perkembangan tasawwuf pada abad kedua Hijriyyah. Sosok sufi penting yang dikenal dengan ajaran cinta atau mahabbah tak lain adalah wali agung perempuan Rabi’a al-‘Adawiyyah yang hidup pada abad kedua Hijriyyah (w. kira-kira 801 M).
Sebagai catatan kecil, Rabi’ ia hidup pada generasi sebelum Imam Syafi’i (w. 820 M). Ini menunjukkan bahwa ajaran-ajaran tasawwuf sudah mulai dikembangkan dalam waktu yang bersamaan, atau bahkan lebih dahulu dari ilmu fikih. Karena itu sangat keliru sekali mereka yang beranggapan bahwa tasawwuf lahir sebagai respon atas ilmu lahir-syariat-fikih yang kaku, dan demikian secara kronologis tasawwuf berkembang lebih belakangan daripada fikih.
Pandangan ini jelas keliru, sebab tokoh-tokoh yang mengembangkan tradisi spiritualitas Islam pada masa-masa awal hidup sezaman dengan tokoh-tokoh pendiri ilmu fikih.
Kembali ke tema pokok mengenai mahabbah: jelas sekali bahwa dimensi keindahan Tuhan sangat mendapatkan perhatian dalam tasawwuf ketimbang dimensi lain. Karena itu, mereka yang hendak menggali “al-jawanib al-intsiyyah” (الجوانب الإنثية) atau dimensi-dimensi keperempuanan/feminin dalam Islam biasanya akan bergegas lari ke tasawwuf. Sebab di sanalah aspek keindahan dan keperempuanan sangat menonjol sebagai “mode of existence”, cara mengada dan cara beragama.
Bahwa tasawwuf diidentikkan dengan aspek keindahan dan keperempuanan ini sangat disadari oleh kalangan sufi sendiri. Seorang tokoh sufi penting dari abad kelima Hijriyyah yang berjasa besar merumuskan dan mensistematisir ajaran-ajaran tasawwuf, yaitu Imam al-Qusyairi (w. 1074), menggambarkan tasawwuf dalam kitabnya yang masyhur “al-Risalah al-Qusyairiyyah” seperti ini:
أما الخيام فإنها كخيامهم
وأرى نساء الحى غير نساءها
Tenda-tenda itu tentu
Masih seperti tenda yang dahulu
Tetapi perempuan-perempuan itu
Bukanlah perempuan yang sama
Yang pernah ada di sana dahulu
Kehidupan tasawwuf digambarkan oleh Imam al-Qusyairi seperti kehidupan di bawah tenda yang amat sederhana di padang pasir, jauh dari kemewahan dan glamor kehidupan di kota-kota pusat peradaban saat itu, seperti Baghdad, Syam, Kairo, Basrah, Nishapur, Qairawan, dll. Sementara para sufi dimetaforkan seperti perempuan-perempuan cantik yang tinggal di tenda-tenda itu.
Saat menulis kitabnya yang masyhur ini, Imam al-Qusyairi mengeluhkan semacam kehidupan spiritual di kalangan umat Islam yang sedang merosot. Praktek-praktek luaran beragama (dimetaforkan dengan tenda dalam syair di atas) sudah kehilangan roh utama, yaitu keindahan-keperempuanan. Dengan kata lain, tak ada tasawwuf dan kehidupan spiritual tanpa semangat dasar yang melandasinya: yaitu keindahan cinta. Tasawwuf tanpa mahabbah di dasar ceruknya, akan sama dengan “tenda tanpa perempuan di dalamnya”.
Menegakkan tenda tentu saja penting. Tetapi yang jauh lebih penting adalah menghadirkan “perempuan” di dalamnya. Itulah mahabbah. Demikian kira-kira cara pandang kaum sufi tentang “mode of existence”, cara hidup dan cara beragama.
Sekian.
——
Catatan:
Semula, judul esei ini adalah “Tenda dan ‘perempuan cantik’”. Kemudian, kata “cantik” dengan sengaja saya “busak” dan hapuskan, baik dari judul maupun teks, karena mengandung pengertian yang mengelirukan (misleading).
Penulis: Ulil Abshar Abdalla, Pengampu Ngaji Ihya’.