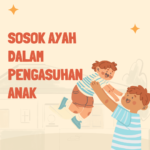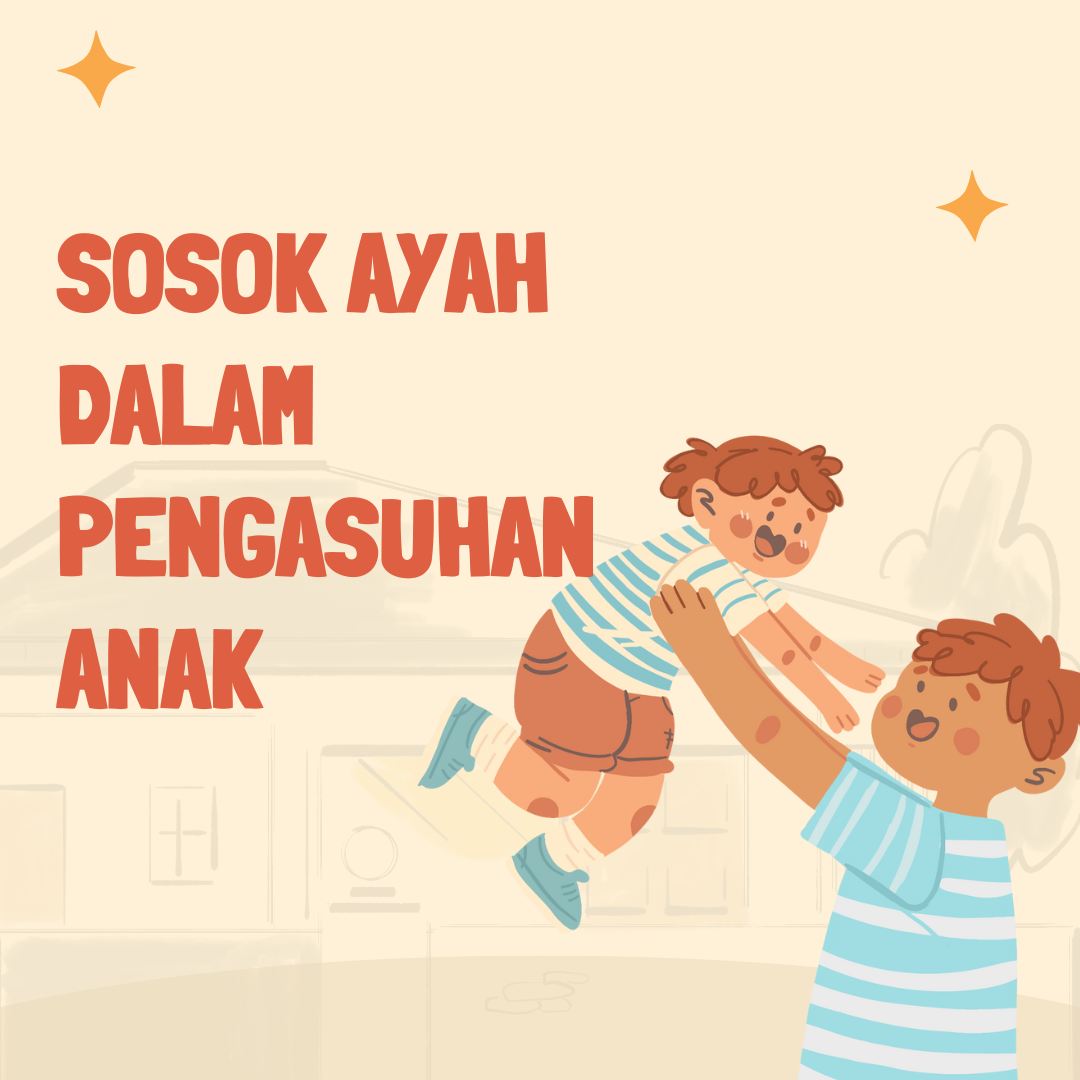Urgensi Eksistensi Masyaikh Perempuan di Lingkungan Pesantren
Rozi Adhar (Kontributor PW Fatayat NU DIY)
Kehadiran akan guru dan pengasuh perempuan menjadi keniscayaan, ketika dominasi masyaikh laki-laki di ma’had (pesantren) telah mengakar kuat di Indonesia. Kuatnya otoritas pengasuh laki-laki ini berpengaruh pada corak khazanah keilmuan yang berwajah maskulin, termasuk fikih. Beberapa masyaikh memiliki lebih dari satu istri, dengan dalil bahwa surga istri merupakan kewenangan suami.
Dalil seperti ini menjadi legitimasi bagi laki-laki untuk melihat dan bersikap dari satu sisi sesuai dengan kehendaknya. Keputusan sepihak tersebut berdampak pada diskriminasi perempuan. Perempuan menjadi tersakiti, namun tidak memiliki keberanian untuk menyatakan isi hatinya karena “alasan fikih” yakni takut kualat pada suami.
Untuk itu, penambahan kuantitas maupun kualitas para masyaikh perempuan menjadi isu serius yang harus segera direalisasikan. Hal ini menjadi agenda penting untuk ditindaklanjuti mengingat beberapa kajian fiqih membutuhkan pemahaman dan pengalaman perempuan secara khusus yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Di Ma’had Darul Qur’an wal Hadits Lombok Timur misalkan, pengadaan masyaikh perempuan masih pada tahap wacana, sehingga kelas fiqih di kelas banat diampu oleh guru laki-laki.
Hal ini tidak menjadi persoalan ketika pembahasannya berkaitan dengan syariat umum, maupun muamalah seperti berdagang. Namun pada beberapa materi fikih yang semestinya melibatkan banyak pandangan perempuan seperti mandi wajib, pernikahan dan poligami, eksistensi masyaikh perempuan sangat dibutuhkan tidak hanya sebagai penyeimbang, namun juga sebagai sumber utama dalam pengambilan sikap.
Sebagai rujukan, Islam memperbolehkan perempuan untuk menjadi pengajar sebagaimana laki-laki. Kewajiban untuk menyebarkan ilmu berlaku bagi perempuan dan laki-laki. Pada masa periode pertama kejayaan Islam, banyak perempuan yang menjadi perawi hadits dan ahli tasawuf. Dalam kalangan Hanafi, kita mengenal Fathimah sebagai ulama fikih dari keturunan Syekh Muhammad yang mahar pernikahannya adalah kitab syarah karya ayahnya. Pandangan-pandangan Fathimah dalam dunia fikih tidak hanya menjadi bacaan utama mazhab Hanafi, tapi juga mendapat penghormatan tinggi dari raja di negerinya.
Pentingnya perspektif perempuan ini juga dirasakan pada pendidikan masa kini. Penulis menggali pengalaman beberapa perempuan yang pernah mengikuti kelas fikih yang diampu pria. Mereka merasa tidak nyaman ketika bertanya kepada masyaikh lelaki dalam bab-bab fikih yang membahas praktik yang berkaitan alat-alat vital. Meskipun perbedaan jenis kelamin antara guru dan murid bukan suatu masalah dalam ranah pendidikan, namun hal ini menjadikan santri perempuan merasa tidak leluasa untuk bertanya. Hal tersebut tentu akan berdampak pada kurangnya kedalaman materi yang disampaikan di kelas.
Perbedaan jenis kelamin ini pun berdampak pada berbedanya penekanan penafsiran dalam suatu dalil sesuai dengan kepentingan gender yang menyampaikan. Misalnya terkait poligami, jika diringkas dari berbagai kitab, bahwa poligami itu boleh, asal adil. Ketika dibahas oleh masyaikh pria, penekanannya pada hukum kebolehan dari poligami, namun dari sisi masyaikh perempuan, penekanannya adalah pada kata “adil”. Penekanan “adil” ini sangat penting digaungkan untuk menjadi pertimbangan utama, mengingat hal tersebut sangat sukar dilakukan karena takarannya yang tidak pernah jelas.
Adil menurut laki-laki belum tentu adil menurut perempuan. Jeritan-jeritan hati perempuan yang dipoligami sangat penting untuk diperdengarkan dalam rangka menyadarkan banyak pihak. Itu bisa dilakukan jika yang membahas poligami adalah masyaikh perempuan, ataupun yang memiliki perspektif perempuan. Argumentasi lain adalah bahwa masyaikh pria, dengan proses belajar, boleh jadi menguasai bahasan thaharah (bersuci) secara komprehensif, namun tetap saja mereka tidak pernah mengalami pengalaman sebagai perempuan.
Misalnya, pada bab seperti haid, mereka bisa saja menjelaskan secara detail berdasarkan bacaan, namun terbatas pada penjelasan teoritis. Banyak hal detail yang sifatnya empiris, hanya bisa dipahami dan dijelaskan oleh perempuan. Ketika haid datang masyaikh pria tentu bisa menerangkan apa-apa yang mesti dilakukan sesuai dengan panduan yang diketahui. Tapi, yang menyaksikan jenis darah haid, mengalami rasanya haid, terutama di hari pertama adalah perempuan. Dalam hal ini, penjelasan terkait trik-trik menahan rasa sakit, atau tips-tips baik di hari awal haid hanya bisa diterangkan dengan perasaan oleh masyaikh perempuan.
Dari uraian di atas, terlihat betapa pentingnya kehadiran masyaikh perempuan di tingkat ma’had. Untuk mewujudkan hal ini, beberapa upaya bisa dilakukan secara beragam. Salah satu cara adalah dengan menambah kuota masyaikh perempuan di ma’had. Sementara bagi ma’had yang belum memiliki sumber dayanya terbatas, seperti beberapa ma’had di Lombok Timur, maka bisa melalui kebijakan afirmasi yaitu mendatangkan pengajar perempuan dari luar pondok untuk menerangkan beberapa kajian fikih.
Selanjutnya dipersiapkan supaya ke depan ada pengajar tetap perempuan. Sebagai upaya benchmarking, ma’had tersebut bisa mengadakan studi banding ke ma’had yang kuota pengajar perempuannya sudah memadai sehingga mendapatkan inspirasi dalam rangka peningkatan jumlah guru perempuan. Pada akhirnya, tulisan ini tidak sedikitpun menyudutkan atau meremehkan masyaikh lelaki dalam menyampaikan kajian-kajian fikih perempuan. Penulis menghormati betul para masyaikh yang telah menghabiskan waktu lama dan membaca banyak sekali kitab untuk belajar fikih.
Sejauh ini, mereka telah berjasa mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menerangkan berbagai masalah fikih di pengajian-pengajian maupun di ma’had. Hanya saja, untuk mereduksi bias gender dalam menerangkan masalah kewanitaan, maka perlu ada ruang yang lebih luas bagi para perempuan untuk bersuara. Perempuanlah yang lebih memahami persoalan perempuan.