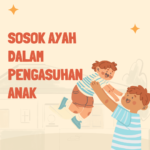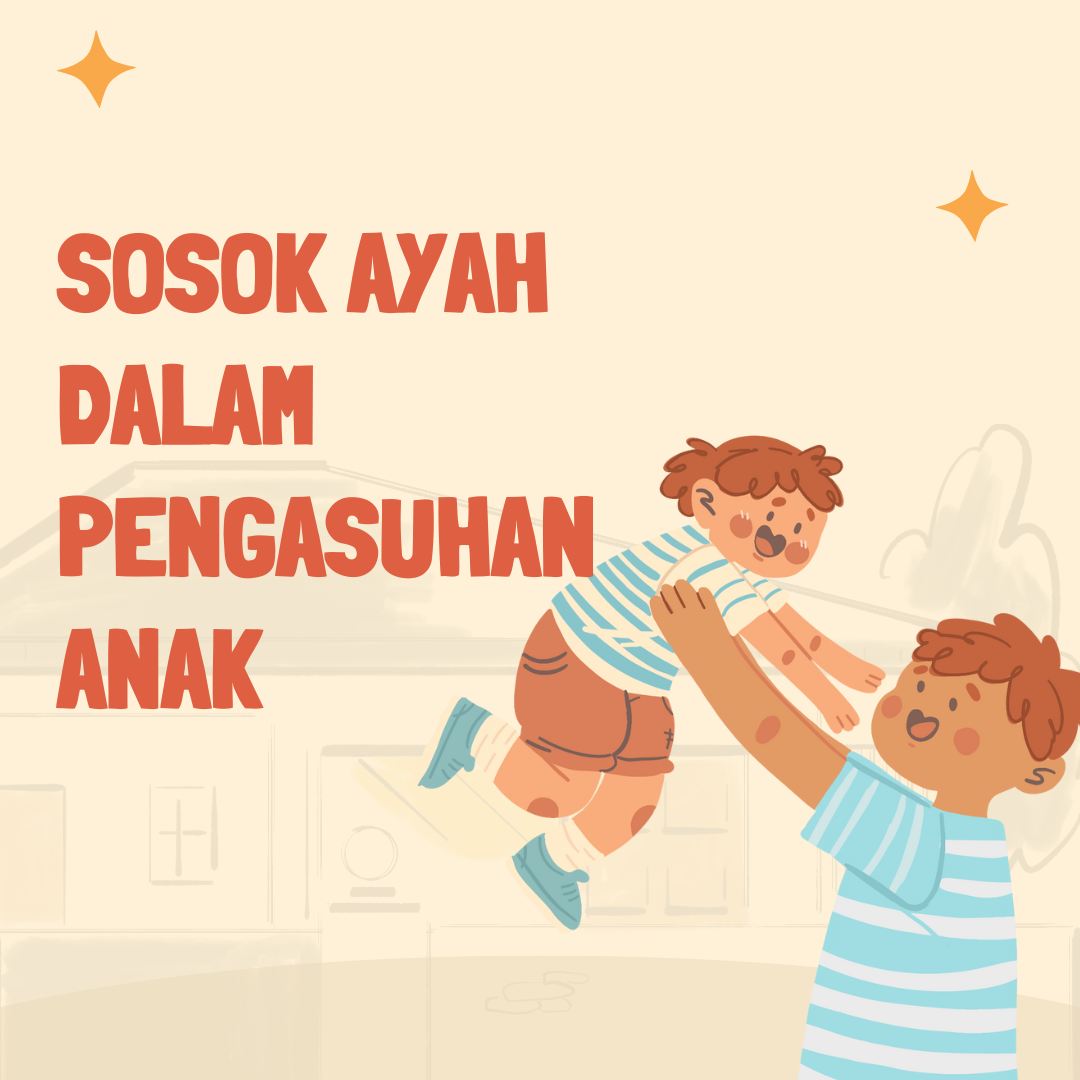Niswatin Faoziah
Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki akar sejarah panjang dan peran strategis dalam pembentukan karakter bangsa. Sejak awal kemunculannya, pesantren tidak hanya menjadi pusat pengajaran ilmu agama, tetapi ruang pembentukan karakter dan penjaga nilai-nilai moral. Kekuatan pesantren terletak pada kemampuannya menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik (al-muhafadzatu ‘ala al-qodimish shalih wa al-akhdzu bi al jadid al-aslah), memadukan nilai keagamaan dengan kearifan lokal, serta menciptakan harmoni antara ajaran yang bersifat transenden dengan kehidupan sosial yang majemuk.
Di tengah konteks masyarakat Indonesia yang plural dan dinamis, pesantren menyimpan potensi besar untuk menjadi motor penggerak pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Potensi ini penting untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya memiliki kompetensi keilmuan, tetapi juga kebijaksanaan moral dan kemampuan berinteraksi secara konstruktif dengan keberagaman.
Namun, di era yang ditandai dengan percepatan teknologi, globalisasi dan perubahan sosial yang masif, pesantren memiliki tantangan baru yang kompleks. Bagaimana pesantren dapat mempertahankan tradisi keilmuan yang mendalam sekaligus merespons tuntunan dunia modern? Tulisan ini membahas sejumlah tantangan utama yang dihadapi pesantren saat ini, sekaligus menawarkan alternatif langkah adaptasi agar keberadaannya tetap relevan di tengah perubahan zaman.

1. Digitalisasi dan Teknologi Informasi
Revolusi digital telah membuka peluang bagi pesantren untuk memperluas akses informasi, memperkuat jejaring pembelajaran, dan memfasilitasi metode pengajaran jarak jauh. Salah satu kekuatan pesantren adalah kemampuannya mengadopsi unsur-unsur modern tanpa menghilangkan inti ajaran.
Namun, gelombang digitalisasi juga membawa resiko seperti penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, paparan ideologi ekstrem secara daring, serta perubahan pola belajar akibat budaya serba cepat yang menggerus kedalaman berpikir. Di sinilah pesantren ditantang untuk membekali santri dengan literasi digital yang beretika.
Prinsip-prinsip Islam seperti tahqiq al-masadir (verifikasi sumber) dalam usul fiqh dan adab al-ikhtilaf (etika berbeda pendapat) harus menjadi fondasi dalam menghadapi dunia digital. Pesantren perlu memberikan ruang dimana teknologi modern dan nilai- nilai keislaman berpadu secara harmonis, sehingga integrasi inovasi dan tradisi dapat dilakukan secara kontekstual.
2. Dilema Kurikulum:Di tengah Tarikan Tradisi dan Modernitas
Pesantren salaf umumnya unggul dalam kajian kitab kuning dengan metode bandhongan dan sorogan, tetapi sering dinilai tertinggal dalam penguasaan keterampilan abad ke-21. Di sisi lain, pesantren modern yang mengadopsi kurikulum nasional kadang mengurangi intensitas pendalaman spiritual. Dalam konteks ini, keberhasilan pesantren terletak pada kemampuannya mempertahankan cultural capital berupa otoritas keilmuan dan nilai-nilai tradisi, sambil menyesuaikan diri dengan konteks sosial.
Model kurikulum hybrid dapat menjadi salah satu alternatif. Kurikulum hybrid — integrasi antara kajian klasik di pesantren dengan STEM (Sains, Teknologi, Teknik dan Matematika), dan soft skill seperti kewirausaha, atau literasi media — sejalan dengan pendidikan Islam kontekstual diharapkan mampu merespons isu-isu global seperti keberlanjutan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keadilan sosial. Sehingga pesantren tidak hanya mencetak ahli agama, tetapi juga ilmuwan, pemimpin dan pelaku perubahan (agent of change) yang berakar pada nilai- nilai Islam.
3. Inklusivitas dalam Konteks Multikultural
Dalam kerangka masyarakat multikultural, pesantren memiliki potensi sebagai ruang interaksi lintas identitas. Akan tetapi, homogenitas dalam aspek mazhab, etnis, atau budaya masih sering dijumpai. Pendidikan Islam seyogyanya mengajarkan para santri untuk hidup selaras dalam keragaman, bukan hanya mentoleransi, tetapi secara aktif terlibat dalam membangun harmoni dan kohesi sosial.
Dalam Al-Quran prinsip ta’aruf (saling mengenal, QS. Al-Hujurat: 13) dan al musawa (kesetaraan, QS. Al Hujurat:10) menjadi landasan teologis, bahwa perbedaan bukanlah ancaman namun perbedaan adalah keniscayaan dan anugerah yang harus dikelola dengan bijak. Pendidikan Islam yang sehat mendorong pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman.
Strategi seperti program pertukaran santri antar-pesantren dengan latar berbeda, kajian ayat-ayat yang menekankan prinsip ta’aruf (saling mengenal), dan partisipasi dalam dialog antaragama dapat memperluas perspektif santri. Secara historis, pesantren memiliki keterbukaan terhadap unsur budaya lokal—warisan ini dapat dihidupkan kembali sebagai modal sosial untuk memperkuat kohesi masyarakat.
4. Relasi Otoritas dan Praktik Pendidikan
Struktur hierarkis antara kiai dan santri umumnya memberikan stabilitas dalam sistem pesantren, namun dalam beberapa kasus dapat membatasi ruang untuk dialog dua arah. Pola komunikasi yang dominan satu arah ini berpotensi mengurangi kesempatan bagi santri untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan tersebut terkadang kurang menonjolkan aspek humanisasi yang menjadi salah satu prinsip penting dalam Islam.
Oleh karena itu, penerapan metode seperti trauma-informed teaching atau menggantikan hukuman fisik dengan pendekatan reflektif seperti muhasabah (evalusi diri) atau mediasi konflik, dan pembentukan dewan santri yang diberi ruang untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan dapat membantu menciptakan suasana belajar yang lebih inklusif dan partisipatif tanpa mengurangi wibawa pengasuh. Dalam konteks ini, hubungan guru-santri yang didasarkan pada saling menghormati diyakini dapat memperkuat efektivitas pendidikan di pesantren.
5. Resistensi terhadap Perubahan dan Tantangan Kapasitas Sumber Daya
Pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis nilai-nilai keislaman menghadapi dilema yang kompleks dalam merespons perubahan zaman. Di satu sisi, terdapat kekhawatiran dari sebagian pengasuh dan pengajar yang memandang inovasi dengan sikap skeptis karena khawatir dapat mengurangi kemurnian tradisi pesantren. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi menjadi hambatan nyata dalam proses transformasi kelembagaan.
Resistensi terhadap perubahan ini sebaiknya tidak dimaknai semata-mata sebagai penolakan, melainkan sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga identitas keilmuan dan otoritas moral pesantren. Secara historis, pesantren telah menunjukkan kemampuan adaptasi yang cukup fleksibel—misalnya melalui penerimaan metode pembelajaran modern sambil tetap mempertahankan kajian kitab kuning sebagai inti pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip wa al-akhdzu bi al-jadīd al-aṣlaḥ (“mengambil yang baru dan lebih maslahat”) sejatinya telah menjadi bagian dari dinamika perkembangan pesantren.
Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa langkah strategis dapat ditempuh, seperti memberikan pelatihan teknologi bagi guru, membangun jejaring dengan lembaga lain seperti perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat, serta memanfaatkan pengaruh tokoh-tokoh kharismatik sebagai agen perubahan (change agents). Upaya ini tidak hanya akan mempercepat penerimaan inovasi, tetapi juga memastikan bahwa pembaruan tetap sejalan dengan nilai-nilai inti pesantren.
Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi pesantren — mulai dari digitalisasi hingga resistensi terhadap perubahan — sejatinya menjadi momentum untuk menguji kemampuan lembaga ini dalam menyeimbangkan antara pelestarian warisan tradisi dan pemenuhan tuntutan zaman.
Prinsip tawazun (keseimbangan) dapat dijadikan pedoman agar teknologi dimanfaatkan secara bijaksana sebagai sarana, bukan tujuan; multikulturalisme dipandang sebagai bagian dari sunnatullah yang memperkaya wawasan dan pengalaman; serta pembaruan dilaksanakan dengan penuh penghormatan dan sensitivitas terhadap konteks historis serta nilai-nilai yang telah mengakar.
Dengan pendekatan ini, pesantren memiliki peluang untuk mempertahankan peran strategisnya sebagai institusi yang tidak hanya membentuk pemahaman keislaman yang mendalam, tetapi juga menjadi agen integrasi sosial dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan. Posisi ini menguatkan pesantren sebagai ruang dialog antara tradisi dan modernitas, sekaligus menjembatani kebutuhan umat di era perubahan yang semakin cepat.
***
Penulis adalah Bendahara PW Fatayat NU DIY dan Dosen ISQI Sunan Pandanaran, Yogyakarta